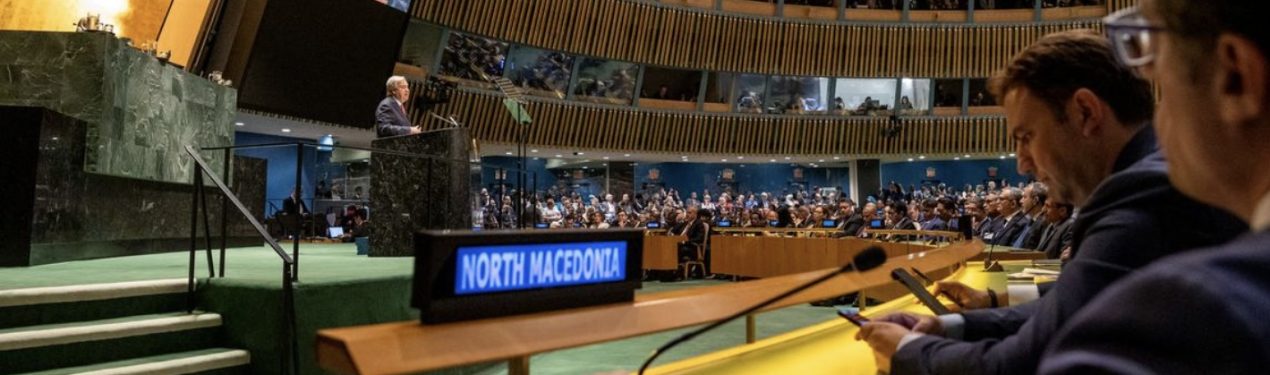Analisis Buku Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity oleh Daron Acemoglu dan Simon Johnson
oleh: Analisis Buku Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity oleh Daron Acemoglu dan Simon Johnson
oleh: MYR Agung Sidayu – Yayasan Pendidikan Indonesia (YPI)
Yayasan Pendidikan Indonesia (YPI), sebagai lembaga nirlaba yang fokus pada peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pemahaman isu-isu global di Indonesia, menyajikan analisis buku ini untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Buku karya Daron Acemoglu (pemenang Nobel Ekonomi 2024) dan Simon Johnson ini relevan bagi kita, karena membahas bagaimana teknologi—termasuk AI—dapat memperburuk ketimpangan jika tidak dikelola dengan bijak, sementara Indonesia sedang bertransformasi digital. Analisis ini bertujuan mendorong diskusi di kalangan pendidik, pemimpin muda, dan pembuat kebijakan untuk memastikan kemajuan teknologi mendukung kesejahteraan bersama, bukan hanya elite.
Ringkasan Singkat Buku
Buku setebal lebih dari 500 halaman ini menelusuri sejarah seribu tahun perubahan teknologi, dari Abad Pertengahan hingga era AI modern. Acemoglu dan Johnson menantang narasi “teknologi selalu membawa kemakmuran otomatis”. Mereka berargumen bahwa kemajuan teknologi bergantung pada pilihan sosial dan kekuasaan: siapa yang mengendalikan inovasi, dan bagaimana manfaatnya didistribusikan. Teknologi bisa mengotomatisasi pekerjaan (menyebabkan pengangguran dan ketimpangan) atau melengkapi kemampuan manusia (menciptakan lapangan kerja baru dan kesejahteraan luas). Tanpa intervensi demokratis, seperti kebijakan pro-buruh dan regulasi, teknologi justru memperkuat elite, seperti yang terlihat pada Revolusi Industri Awal atau boom digital saat ini.
Contoh kunci:
• Abad Pertengahan: Inovasi pertanian meningkatkan produksi, tapi manfaatnya jatuh ke tangan bangsawan untuk perang dan katedral, sementara petani menderita kelaparan.
• Revolusi Industri (abad 18-19): Mesin uap dan pabrik tekstil menaikkan output, tapi upah pekerja stagnan atau turun, dengan eksploitasi anak dan kondisi kerja buruk selama puluhan tahun. Baru setelah reformasi buruh dan serikat pekerja, manfaatnya merata.
• Era Modern: Internet dan AI menciptakan kekayaan, tapi sejak 1970-an, produktivitas AS naik sementara upah stagnan, memperlebar kesenjangan. Buku ini memperingatkan AI bisa memperburuk ini jika diprioritaskan untuk penggantian pekerja, bukan peningkatan keterampilan.
Tesis utama: Kemakmuran bersama bukan hasil alami teknologi, melainkan hasil perjuangan kekuasaan—melalui koersi (seperti perbudakan) atau persuasi (ide pro-bisnis). Buku ini berakhir optimis: kita bisa mengarahkan inovasi ke arah yang inklusif melalui pajak otomatisasi, subsidi R&D pro-manusia, dan penguatan demokrasi.
Analisis Kritis: Kekuatan dan Kelemahan
Kekuatan Buku:
• Pendekatan Historis yang Kaya: Dengan contoh dari sejarah global, buku ini membuktikan bahwa “ilusi kemajuan” sering menipu—teknologi netral, tapi kekuasaan menentukan dampaknya. Ini relevan untuk Indonesia, di mana digitalisasi (seperti Gojek atau e-commerce) menciptakan lapangan kerja baru, tapi juga menggusur pekerja informal tanpa jaring pengaman.
• Relevansi dengan AI dan Ketimpangan: Acemoglu memperingatkan AI bisa menciptakan “masyarakat dua tingkat” di mana elite tech (seperti di Silicon Valley) meraup untung, sementara mayoritas kehilangan bargaining power. Di Indonesia, dengan tingkat unionisasi rendah (~7%) dan ketergantungan pada sektor rentan, ini bisa memperburuk kemiskinan struktural.
• Rekomendasi Praktis: Saran seperti “pajak software lebih tinggi daripada tenaga kerja” dan subsidi pendidikan seumur hidup selaras dengan agenda YPI untuk pendidikan vokasi dan literasi digital. Ini bisa diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mengarahkan AI ke sektor pendidikan dan kesehatan, bukan hanya pengawasan.
Kelemahan Buku:
• Interpretasi Historis yang Kontroversial: Kritikus seperti Noah Smith menilai buku melebih-lebihkan dampak negatif, misalnya meremehkan Haber-Bosch (proses pupuk sintetis yang menyelamatkan miliaran nyawa, meski juga digunakan untuk senjata kimia). Di konteks Indonesia, ini mirip kritik terhadap Green Revolution yang meningkatkan produksi padi tapi merusak lingkungan tanpa kebijakan pendukung.
• Kurangnya Bukti Empiris Kuat: Buku kurang kutipan data spesifik untuk “mengarahkan inovasi”, membuat solusi terasa abstrak. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, di mana akses teknologi tidak merata (hanya 60% populasi terhubung internet), buku ini kurang membahas adaptasi lokal, seperti bagaimana UMKM bisa memanfaatkan AI tanpa infrastruktur.
• Optimisme yang Hati-hati: Meski menekankan peran demokrasi, buku kurang menyoroti risiko otoritarianisme teknologi (seperti pengawasan digital di China), yang relevan bagi kita di tengah isu privasi data di platform nasional.
Implikasi untuk Indonesia dan Rekomendasi YPI
Buku ini seperti cermin bagi Indonesia: kita punya potensi teknologi tinggi (peringkat 4 ASEAN di indeks inovasi global 2024), tapi ketimpangan Gini 0.38 menunjukkan manfaat belum merata. AI bisa menggantikan 20-30% pekerjaan di sektor manufaktur dan layanan (menurut proyeksi ILO), tapi juga menciptakan peluang di pendidikan (misalnya, AI tutor untuk daerah terpencil). Tanpa aksi, kita berisiko “keterpurukan AI” seperti yang diperingatkan Acemoglu—di mana oligarki digital mendominasi, mirip era kolonial di mana inovasi Eropa dieksploitasi tanpa manfaat bagi rakyat.
Rekomendasi YPI untuk Pendidikan dan Kebijakan:
1. Integrasikan ke Kurikulum: Masukkan analisis teknologi inklusif ke mata pelajaran Ekonomi dan Sejarah SMA, dengan studi kasus lokal seperti dampak fintech pada petani.
2. Program Pelatihan Guru: Latih 10.000 guru di 2026 tentang “AI Pro-Pekerja”, bekerja sama dengan Kemdikbud untuk modul berbasis buku ini.
3. Advokasi Kebijakan: Dorong pemerintah terapkan “Pajak Digital Progresif” untuk mendanai beasiswa vokasi, dan bentuk forum nasional buruh-teknologi seperti yang disarankan Acemoglu.
4. Penelitian Lanjutan: YPI akan inisiasi studi tentang dampak AI di sektor pendidikan Indonesia, terinspirasi buku ini, untuk publikasi 2026.
Power and Progress bukan hanya buku ekonomi, tapi panggilan untuk aksi kolektif. Seperti kata Acemoglu, “Ini kesempatan terakhir kita untuk bangun.” YPI mengajak semua pihak berkontribusi agar teknologi menjadi alat emansipasi, bukan penindas.
Referensi Tambahan:
• Acemoglu, D. & Johnson, S. (2023). Power and Progress. PublicAffairs.
• Bedah Buku di Unika Atma Jaya (Mei 2025), yang menyoroti relevansi demokrasi dalam pengelolaan teknologi.
• Kritik dari The Guardian dan Noah Smith untuk perspektif seimbang.Yayasan Pendidikan Indonesia (YPI)
Yayasan Pendidikan Indonesia (YPI), sebagai lembaga nirlaba yang fokus pada peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pemahaman isu-isu global di Indonesia, menyajikan analisis buku ini untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Buku karya Daron Acemoglu (pemenang Nobel Ekonomi 2024) dan Simon Johnson ini relevan bagi kita, karena membahas bagaimana teknologi—termasuk AI—dapat memperburuk ketimpangan jika tidak dikelola dengan bijak, sementara Indonesia sedang bertransformasi digital. Analisis ini bertujuan mendorong diskusi di kalangan pendidik, pemimpin muda, dan pembuat kebijakan untuk memastikan kemajuan teknologi mendukung kesejahteraan bersama, bukan hanya elite.
Ringkasan Singkat Buku
Buku setebal lebih dari 500 halaman ini menelusuri sejarah seribu tahun perubahan teknologi, dari Abad Pertengahan hingga era AI modern. Acemoglu dan Johnson menantang narasi “teknologi selalu membawa kemakmuran otomatis”. Mereka berargumen bahwa kemajuan teknologi bergantung pada pilihan sosial dan kekuasaan: siapa yang mengendalikan inovasi, dan bagaimana manfaatnya didistribusikan. Teknologi bisa mengotomatisasi pekerjaan (menyebabkan pengangguran dan ketimpangan) atau melengkapi kemampuan manusia (menciptakan lapangan kerja baru dan kesejahteraan luas). Tanpa intervensi demokratis, seperti kebijakan pro-buruh dan regulasi, teknologi justru memperkuat elite, seperti yang terlihat pada Revolusi Industri Awal atau boom digital saat ini.
Contoh kunci:
• Abad Pertengahan: Inovasi pertanian meningkatkan produksi, tapi manfaatnya jatuh ke tangan bangsawan untuk perang dan katedral, sementara petani menderita kelaparan.
• Revolusi Industri (abad 18-19): Mesin uap dan pabrik tekstil menaikkan output, tapi upah pekerja stagnan atau turun, dengan eksploitasi anak dan kondisi kerja buruk selama puluhan tahun. Baru setelah reformasi buruh dan serikat pekerja, manfaatnya merata.
• Era Modern: Internet dan AI menciptakan kekayaan, tapi sejak 1970-an, produktivitas AS naik sementara upah stagnan, memperlebar kesenjangan. Buku ini memperingatkan AI bisa memperburuk ini jika diprioritaskan untuk penggantian pekerja, bukan peningkatan keterampilan.
Tesis utama: Kemakmuran bersama bukan hasil alami teknologi, melainkan hasil perjuangan kekuasaan—melalui koersi (seperti perbudakan) atau persuasi (ide pro-bisnis). Buku ini berakhir optimis: kita bisa mengarahkan inovasi ke arah yang inklusif melalui pajak otomatisasi, subsidi R&D pro-manusia, dan penguatan demokrasi.
Analisis Kritis: Kekuatan dan Kelemahan
Kekuatan Buku:
• Pendekatan Historis yang Kaya: Dengan contoh dari sejarah global, buku ini membuktikan bahwa “ilusi kemajuan” sering menipu—teknologi netral, tapi kekuasaan menentukan dampaknya. Ini relevan untuk Indonesia, di mana digitalisasi (seperti Gojek atau e-commerce) menciptakan lapangan kerja baru, tapi juga menggusur pekerja informal tanpa jaring pengaman.
• Relevansi dengan AI dan Ketimpangan: Acemoglu memperingatkan AI bisa menciptakan “masyarakat dua tingkat” di mana elite tech (seperti di Silicon Valley) meraup untung, sementara mayoritas kehilangan bargaining power. Di Indonesia, dengan tingkat unionisasi rendah (~7%) dan ketergantungan pada sektor rentan, ini bisa memperburuk kemiskinan struktural.
• Rekomendasi Praktis: Saran seperti “pajak software lebih tinggi daripada tenaga kerja” dan subsidi pendidikan seumur hidup selaras dengan agenda YPI untuk pendidikan vokasi dan literasi digital. Ini bisa diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mengarahkan AI ke sektor pendidikan dan kesehatan, bukan hanya pengawasan.
Kelemahan Buku:
• Interpretasi Historis yang Kontroversial: Kritikus seperti Noah Smith menilai buku melebih-lebihkan dampak negatif, misalnya meremehkan Haber-Bosch (proses pupuk sintetis yang menyelamatkan miliaran nyawa, meski juga digunakan untuk senjata kimia). Di konteks Indonesia, ini mirip kritik terhadap Green Revolution yang meningkatkan produksi padi tapi merusak lingkungan tanpa kebijakan pendukung.
• Kurangnya Bukti Empiris Kuat: Buku kurang kutipan data spesifik untuk “mengarahkan inovasi”, membuat solusi terasa abstrak. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, di mana akses teknologi tidak merata (hanya 60% populasi terhubung internet), buku ini kurang membahas adaptasi lokal, seperti bagaimana UMKM bisa memanfaatkan AI tanpa infrastruktur.
• Optimisme yang Hati-hati: Meski menekankan peran demokrasi, buku kurang menyoroti risiko otoritarianisme teknologi (seperti pengawasan digital di China), yang relevan bagi kita di tengah isu privasi data di platform nasional.
Implikasi untuk Indonesia dan Rekomendasi YPI
Buku ini seperti cermin bagi Indonesia: kita punya potensi teknologi tinggi (peringkat 4 ASEAN di indeks inovasi global 2024), tapi ketimpangan Gini 0.38 menunjukkan manfaat belum merata. AI bisa menggantikan 20-30% pekerjaan di sektor manufaktur dan layanan (menurut proyeksi ILO), tapi juga menciptakan peluang di pendidikan (misalnya, AI tutor untuk daerah terpencil). Tanpa aksi, kita berisiko “keterpurukan AI” seperti yang diperingatkan Acemoglu—di mana oligarki digital mendominasi, mirip era kolonial di mana inovasi Eropa dieksploitasi tanpa manfaat bagi rakyat.
Rekomendasi YPI untuk Pendidikan dan Kebijakan:
1. Integrasikan ke Kurikulum: Masukkan analisis teknologi inklusif ke mata pelajaran Ekonomi dan Sejarah SMA, dengan studi kasus lokal seperti dampak fintech pada petani.
2. Program Pelatihan Guru: Latih 10.000 guru di 2026 tentang “AI Pro-Pekerja”, bekerja sama dengan Kemdikbud untuk modul berbasis buku ini.
3. Advokasi Kebijakan: Dorong pemerintah terapkan “Pajak Digital Progresif” untuk mendanai beasiswa vokasi, dan bentuk forum nasional buruh-teknologi seperti yang disarankan Acemoglu.
4. Penelitian Lanjutan: YPI akan inisiasi studi tentang dampak AI di sektor pendidikan Indonesia, terinspirasi buku ini, untuk publikasi 2026.
Power and Progress bukan hanya buku ekonomi, tapi panggilan untuk aksi kolektif. Seperti kata Acemoglu, “Ini kesempatan terakhir kita untuk bangun.” YPI mengajak semua pihak berkontribusi agar teknologi menjadi alat emansipasi, bukan penindas.
Referensi Tambahan:
• Acemoglu, D. & Johnson, S. (2023). Power and Progress. PublicAffairs.
• Bedah Buku di Unika Atma Jaya (Mei 2025), yang menyoroti relevansi demokrasi dalam pengelolaan teknologi.
• Kritik dari The Guardian dan Noah Smith untuk perspektif seimbang.