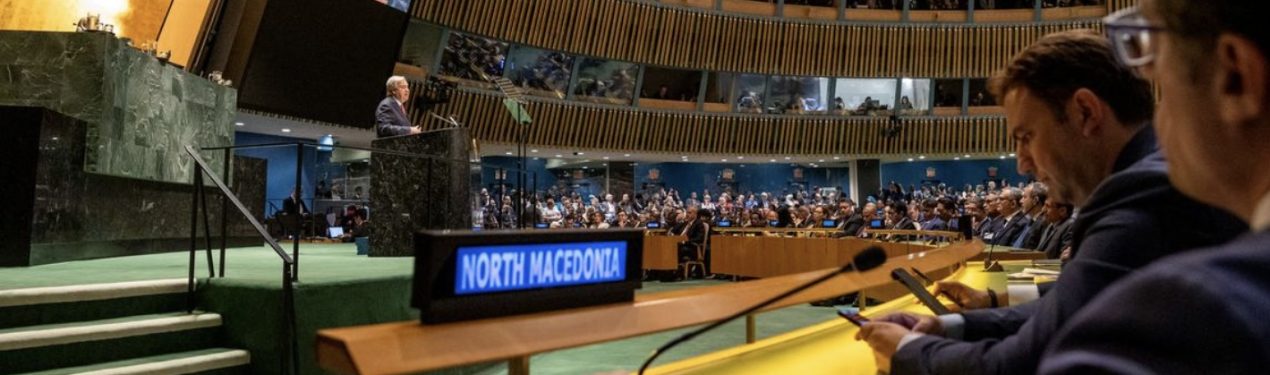Pendidikan di Era Modern: Mengakui Keterampilan Hidup sebagai Fondasi Kesuksesan.
Oleh:
MYR Agung Sidayu
Yayasan Pendidikan Indonesia
Spesial consultative status in ECOSOC
United Nations.
———-
Illustrasi.
Pengalaman pribadi saya sangat menarik, saat mengurus pendaftaran Ikhwan Triatmo dengan Special admission sebagai mature student di Wintec New Zealand tahun 2001.
Di institusi serupa seperti University of Waikato dan lain lain, pelamar berusia 20+ tahun bisa dipertimbangkan untuk masuk program sarjana tanpa memenuhi syarat akademik standar (misalnya, nilai SMA tinggi). Ini sering melibatkan penilaian RPL untuk memverifikasi bahwa pengalaman hidup atau kerja mereka setara. 
Dalam kasus Ikhwan, negosiasi kemungkinan mempercepat proses ini, tapi dasarnya tetap RPL—di mana usia dan pengalaman non-akademik diakui sebagai “prior learning”.
RPL justru dirancang untuk orang yang latar belakang formalnya kurang kuat, tapi punya kekuatan di pengalaman lain. Ini menjelaskan kenapa dia bisa diterima, lalu unggul sebagai mahasiswa terbaik dan lulus cumlaude—bukti bahwa RPL bisa membuka pintu bagi seseorang dengan talenta .
Wintec secara spesifik punya perhatian khusus untuk RPL, di mana mereka menilai bukti seperti portofolio kerja atau wawancara untuk memberikan kredit. lebih lanjut mari kita telaah bersama artikel ini ;
———
Pendahuluan.
Di tengah dinamika perkembangan zaman, dunia pendidikan terus bertransformasi untuk menjawab tantangan global. Salah satu isu yang kerap menjadi sorotan adalah validitas ijazah formal seorang pemimpin. Tak jarang, masyarakat mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan, bahkan hingga menggugatnya di ranah hukum.
Namun, di balik polemik tersebut, dunia pendidikan internasional telah melangkah jauh ke depan, mengakui bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh selembar ijazah, tetapi juga oleh keterampilan hidup (life skills) yang dibangun melalui pengalaman nyata. Pemerintah Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perimbangan dunia pendidikan internasional, sehingga tidak terpaku pada ijazah dalam negeri sebagai satu-satunya tolok ukur dalam penerimaan calon legislatif atau eksekutif, demi mencegah preseden buruk yang dapat merusak kepercayaan publik.
Pendidikan Formal dan Keterampilan Hidup: Dua Sisi Mata Uang.
Pendidikan formal selama ini sering dianggap sebagai tolok ukur utama kompetensi seseorang. Ijazah dari institusi ternama menjadi simbol status, keberhasilan, dan legitimasi dalam dunia profesional, termasuk dalam ranah politik. Namun, realitas modern menunjukkan bahwa dunia kerja dan masyarakat global kini lebih menghargai keterampilan praktis, kemampuan beradaptasi, serta pengalaman yang relevan.
Pendidikan tinggi, baik yang dilakukan secara langsung di kampus (on-campus) maupun melalui pembelajaran jarak jauh (off-campus), telah berevolusi untuk mengakomodasi kebutuhan ini.
Sistem Recognition of Prior Learning (RPL) atau pengakuan pembelajaran sebelumnya, misalnya, memungkinkan individu dengan pengalaman profesional atau keterampilan khusus untuk mendapatkan kredit akademik. Pendekatan ini membuka peluang bagi banyak individu, termasuk calon pemimpin, untuk meningkatkan kualifikasi mereka tanpa harus melalui jalur pendidikan formal yang kaku.
Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan pengakuan terhadap keterampilan dan pengalaman ini dalam menetapkan kriteria kelayakan bagi calon legislatif dan eksekutif, sejalan dengan standar internasional.
Jejak Historis Positif: Pengakuan Pemimpin Autodidak di DPR.
Sejarah parlemen Indonesia mencatat jejak positif dari pengakuan terhadap pemimpin yang mengandalkan pengalaman hidup dan keterampilan autodidak, tanpa terikat kaku pada ijazah formal. Salah satu contoh inspiratif adalah Allahyarham K.H. Najih Ahyat, seorang ulama dan intelektual handal yang menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) pada periode 1999-2004. Sebagai pemangku Pondok Pesantren Maskumambang di Gresik, beliau adalah pemimpin autodidak yang membangun fondasi pendidikan Islam melalui pengalaman langsung dalam membimbing santri dan memimpin komunitas.
Tanpa latar belakang pendidikan sarjana formal, kontribusinya di DPR setara dengan anggota lain yang berpendidikan tinggi, di mana beliau aktif dalam pembahasan isu pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan umat. Keberadaannya di parlemen menjadi bukti bahwa keterampilan hidup—seperti kepemimpinan, pemikiran kritis, dan pengabdian masyarakat—dapat menyamai nilai ijazah sarjana, serta memperkaya diskursus demokrasi dengan perspektif keislaman yang inklusif.
Jejak ini menjadi preseden positif bahwa regulasi pendidikan tidak boleh menghambat talenta seperti K.H. Najih Ahyat, yang justru memperkuat legitimasi DPR sebagai representasi beragamnya masyarakat Indonesia.
Mengapa Memalsukan Ijazah Tidak Lagi Relevan.
Polemik seputar pemalsuan ijazah sering kali muncul karena tekanan sosial dan regulasi yang kaku untuk memiliki gelar formal, terutama dalam konteks pencalonan politik. Persyaratan ijazah dalam negeri sebagai syarat mutlak bagi calon legislatif atau eksekutif kerap mendorong praktik-praktik yang tidak etis, seperti pemalsuan dokumen.
Padahal, dengan perkembangan sistem pendidikan yang inklusif, kebutuhan untuk memalsukan ijazah menjadi tidak relevan. Dunia pendidikan kini mengakui bahwa keterampilan hidup—seperti kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, kepemimpinan, dan kolaborasi—memiliki nilai yang setara, bahkan kadang lebih tinggi, dibandingkan gelar akademik.
Banyak universitas terkemuka di dunia, seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, telah mengadopsi model pendidikan fleksibel. Program seperti online degrees, micro-credentials, dan professional certifications memungkinkan individu untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan jadwal mereka.
Di Indonesia, sejumlah institusi pendidikan tinggi juga mulai mengintegrasikan pendekatan serupa melalui program kuliah daring atau pelatihan berbasis kompetensi. Dengan demikian, pemerintah dapat mengadopsi standar internasional ini untuk memperluas kriteria kelayakan calon pemimpin, sehingga tidak hanya terfokus pada ijazah dalam negeri, tetapi juga pada kompetensi nyata yang telah terbukti.
Contoh Kasus Politik: Polemik Ijazah dalam Pencalonan.
Sejumlah kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana ketergantungan pada ijazah sebagai syarat mutlak dalam pencalonan politik dapat menimbulkan masalah. Berikut adalah beberapa contoh nyata:
- Kasus Pilkada 2020 di Jawa Tengah.
Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, seorang calon bupati dihadapkan pada gugatan hukum karena keabsahan ijazah sarjananya dipertanyakan. Calon tersebut memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat, termasuk pengalaman selama lebih dari 15 tahun dalam mengelola organisasi masyarakat dan memimpin proyek pembangunan lokal yang sukses. Namun, fokus publik dan penyelenggara pemilu tertuju pada keabsahan dokumen pendidikannya, yang menyebabkan proses hukum yang panjang dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Kasus ini menunjukkan bahwa persyaratan ijazah yang kaku dapat mengabaikan kompetensi nyata seorang calon.
- Kasus Pencalonan Legislatif 2019 di Jakarta.
Pada Pemilu 2019, seorang calon legislatif di Jakarta didiskualifikasi karena ijazah sarjananya dari universitas dalam negeri dianggap tidak memenuhi syarat administratif, meskipun ia memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai pengusaha sukses dan pemimpin komunitas yang diakui. Calon ini telah membuktikan kemampuannya dalam memimpin organisasi nirlaba yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, namun aturan yang menekankan ijazah formal menghalanginya untuk berkompetisi. Kasus ini memicu kritik terhadap sistem yang mengesampingkan pengalaman praktis demi formalitas akademik.
- Kasus Pilgub 2017 di Sulawesi Selatan.
Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2017, seorang calon dihadapkan pada tuduhan bahwa ijazahnya tidak sah karena diperoleh dari institusi yang tidak terakreditasi dengan baik. Meskipun calon tersebut memiliki pengalaman panjang sebagai pejabat publik dan rekam jejak yang terbukti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuduhan ini menciptakan polemik yang mengalihkan perhatian dari visi dan programnya. Kasus ini menjadi contoh bagaimana fokus berlebihan pada ijazah dapat merusak proses demokrasi dan menciptakan preseden buruk.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa regulasi yang terlalu kaku soal ijazah dapat menghambat partisipasi individu berkompeten dalam politik, sekaligus mendorong praktik pemalsuan ijazah untuk memenuhi syarat formal. Hal ini tidak hanya merugikan calon yang berkualitas, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Revitalisasi Undang-Undang.
Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjaga supremasi UUD 1945 dan memastikan bahwa undang-undang tidak menghambat perjalanan demokrasi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK berwenang melakukan judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, termasuk memutuskan pembatalan atau revitalisasi norma-norma yang kaku dan tidak inklusif.
Peran ini mencakup pengujian materiil (isi) dan formil (proses pembentukan) undang-undang, sehingga dapat mencegah regulasi yang membatasi hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk dipilih dalam pemilu. MK tidak hanya membatalkan undang-undang yang inkonstitusional, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan dalam jangka waktu tertentu untuk menyelaraskan dengan prinsip demokrasi yang adil dan inklusif.
Dalam konteks syarat pendidikan calon pemimpin, MK dapat merevitalisasi undang-undang seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pilkada dengan mengakui pengakuan ijazah sederajat dari pendidikan internasional dan keterampilan hidup, sehingga tidak lagi menjadi penghalang bagi calon berpengalaman. Hal ini mencegah preseden buruk dan memperkuat integritas demokrasi.
Contoh Kasus Gugatan Ijazah Wakil Presiden Gibran dan Lainnya.
- Kasus Gugatan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (2025)
�Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan utama, di mana seorang warga bernama Subhan Palal menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada September 2025, menyoal keabsahan ijazah SMA Gibran dari Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch, Australia, yang dianggap tidak setara dengan syarat SLTA/sederajat dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.
Gugatan ini menuntut ganti rugi Rp125 triliun dan menyoroti “cacat bawaan” dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah batas usia calon presiden/wakil presiden untuk memungkinkan pencalonan Gibran meskipun usianya di bawah 40 tahun. Meskipun MK menyatakan tidak berwenang mengadili pencalonan secara langsung, pakar seperti Refly Harun mendorong judicial review ke MK untuk merevitalisasi UU Pemilu, agar syarat pendidikan lebih fleksibel dan mengakui kesetaraan internasional, sehingga menghindari gugatan serupa yang merusak kepercayaan publik.
- Kasus Pengujian Syarat Pendidikan Calon Kepala Daerah (2024)
Pada September 2024, warga bernama Zulferinanda mengajukan uji materi ke MK terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada, yang mensyaratkan pendidikan minimal sarjana (S1) bagi calon kepala daerah. Pemohon berargumen bahwa syarat ini diskriminatif dan menghambat demokrasi dengan membatasi partisipasi calon berpengalaman tanpa gelar formal.
Meskipun permohonan dicabut pada Oktober 2024, kasus ini menekankan perlunya MK merevitalisasi norma tersebut melalui putusan inkonstitusional bersyarat, serupa dengan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menurunkan batas usia minimal calon kepala daerah untuk meningkatkan inklusivitas. Kasus ini menjadi preseden bagi pembatalan atau perbaikan regulasi yang kaku.
- Kasus Judicial Review UU Cipta Kerja (2021)
MK membatalkan sebagian UU Cipta Kerja melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2021, menyatakan inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya cacat formil dan materiil, yang berpotensi menghambat hak-hak buruh dan demokrasi partisipatif. MK memerintahkan revisi dalam dua tahun, menunjukkan peran revitalisasi untuk menyelaraskan undang-undang dengan prinsip keadilan sosial.
Kasus-kasus ini mengilustrasikan bagaimana MK dapat membatalkan atau merevitalisasi undang-undang yang menghambat demokrasi, termasuk syarat pendidikan yang tidak adaptif dengan era global.
Peran Pemerintah dalam Menyelaraskan Kebijakan Pendidikan
Untuk menghindari preseden buruk seperti kasus-kasus di atas, pemerintah Indonesia harus mengikuti perimbangan dunia pendidikan internasional.
Salah satu langkah konkret adalah merevisi peraturan yang mengatur syarat pendidikan formal bagi calon legislatif dan eksekutif. Kriteria kelayakan tidak boleh hanya terpaku pada kepemilikan ijazah dalam negeri, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman kerja, keterampilan kepemimpinan, dan kontribusi nyata calon terhadap masyarakat. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan integritas demokrasi.
Selain itu, pemerintah dapat mendorong penerapan sistem RPL secara luas di Indonesia. Dengan mengakui pengalaman dan keterampilan sebagai bagian dari kualifikasi formal, individu yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat—meskipun tanpa gelar akademik tertentu—dapat diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam ranah politik. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pemimpin, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
Peran Yayasan Pendidikan Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya memajukan pendidikan nasional, Yayasan Pendidikan Indonesia berkomitmen untuk mendukung transformasi pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada keterampilan hidup. Kami percaya bahwa pendidikan tidak hanya tentang memperoleh gelar, tetapi juga tentang membekali individu dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan dunia nyata.
Oleh karena itu, kami mendorong pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pengalaman praktis, teknologi, dan pembelajaran berbasis proyek.
Kami juga mendukung penerapan sistem RPL di Indonesia, yang memungkinkan pekerja berpengalaman, pelaku usaha, atau individu dengan keterampilan khusus untuk mendapatkan pengakuan formal atas kompetensi mereka.
Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat mengurangi ketergantungan pada ijazah sebagai satu-satunya bukti kompetensi, sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk calon pemimpin.
Tantangan dan Solusi.
Meskipun dunia pendidikan telah berkembang pesat, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah persepsi masyarakat dan regulasi yang masih memandang ijazah sebagai syarat utama kesuksesan, terutama dalam konteks politik.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi publik tentang nilai keterampilan hidup dan fleksibilitas pendidikan modern. Pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk mempromosikan program-program yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia politik, seperti pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pengembangan soft skills.
Selain itu, penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berbasis keterampilan tetap memiliki standar kualitas yang tinggi. Akreditasi dan pengawasan terhadap program pendidikan daring atau nonformal perlu diperkuat untuk menjaga kredibilitasnya. Dengan demikian, masyarakat dan penyelenggara pemilu dapat mempercayai bahwa kualifikasi yang diperoleh melalui jalur alternatif memiliki nilai yang setara dengan pendidikan formal tradisional.
Kesimpulan.
Menuju Masa Depan Pendidikan yang Inklusif.
Perkembangan dunia pendidikan internasional menunjukkan bahwa masa depan pendidikan adalah tentang fleksibilitas, inklusivitas, dan relevansi. Kita tidak lagi hidup di era di mana ijazah menjadi satu-satunya penentu kesuksesan, baik dalam dunia profesional maupun politik. Keterampilan hidup, pengalaman, dan kemampuan untuk terus belajar adalah aset yang jauh lebih berharga di dunia yang terus berubah.
Yayasan Pendidikan Indonesia mengajak semua pihak—pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan individu—untuk bersama-sama merangkul perubahan ini. Pemerintah, khususnya, memiliki peran strategis untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan dan regulasi pencalonan politik dengan standar internasional, sehingga tidak hanya mengedepankan ijazah dalam negeri, tetapi juga keterampilan dan pengalaman nyata.
Dengan dukungan MK dalam revitalisasi undang-undang, kita dapat memastikan bahwa pendidikan tidak lagi menjadi sekadar formalitas, tetapi menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih cerah dan demokrasi yang lebih berkualitas.